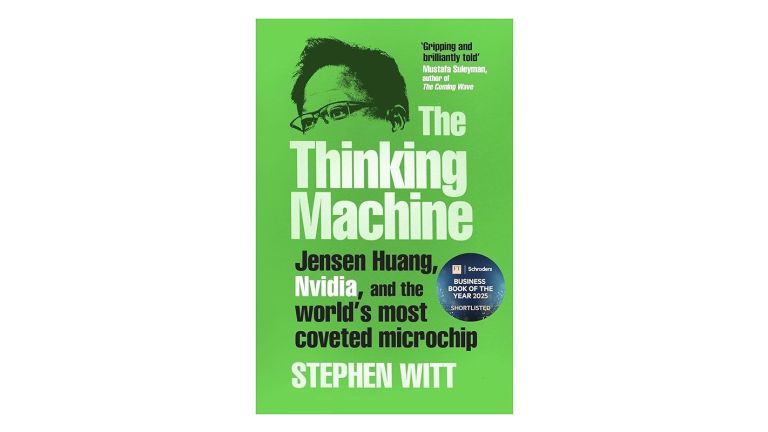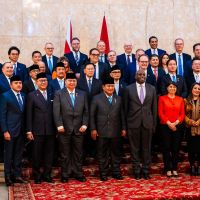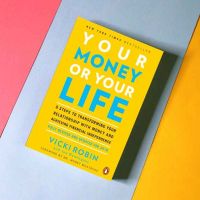Stigma negatif terkait isu lingkungan selalu dialamatkan pada tanaman kelapa sawit. Salah satunya, tanaman yang memiliki nama latin Elaeis guineensis Jacq ini kerap dipersepsikan sebagai tanaman yang boros air.
Beberapa kalangan bahkan menyebut kebun kelapa sawit dianggap sebagai penyebab deforestasi dan mengancam ketersediaan air suatu wilayah. Lantas, benarkah demikian?
Mengutip laman resmi GAPKI, untuk mengetahui anggapan tersebut benar atau salah, penting untuk mengkaji berbagai hasil penelitian terkait dengan perbandingan kebutuhan air konsumtif antara kelapa sawit dan tanaman lainnya.
Sebelumnya, penting untuk diketahui, tanaman dengan ukuran besar pasti membutuhkan lebih banyak air dibandingkan tanaman yang berukuran kecil. Namun, tanaman yang lebih kecil belum tentu menggunakan air lebih efisien dibandingkan tanaman yang lebih besar.
Sebagai contoh, berdasarkan hasil penelitian Coster (1938), menunjukkan bahwa tingkat evapotranspirasi yang menunjukkan kebutuhan air pada kebun kelapa sawit hanya 1,104 mm per tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tanaman bamboo, lamtoro, akasia, sengon, pinus dan karet dengan kisaran kebutuhan air mencapai 1,300-3,000 mm per tahun.
Tak hanya itu, persentase curah hujan yang digunakan oleh kelapa sawit juga lebih lebih rendah dibandingkan dengan mahoni dan pinus. Kemudian, jika dilihat berdasarkan indikator transpirasi atau jumlah air yang menguap ke atmosfer melalui tanaman akibat proses respirasi dan fotosintesis, beberapa studi mengungkapkan bahwa kelapa sawit memiliki nilai yang paling rendah sekitar 0.46 mm per tahun.
Sedangkan, tanaman karet sebesar 2.44 mm per tahun, tanaman kakao sebesar 0.5 sampai 2.2 mm per tahun, dan hutan primer sebesar 1 sampai 1.7 mm per tahun. Berdasarkan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air pada tanaman sawit paling sedikit dibandingkan tanaman lainnya.
Dan pada akhirnya, penelitian yang dilakukan oleh Coster itu menemukan fakta bahwa tanaman sawit yang selama ini dituduh rakus air, ternyata jauh lebih hemat dibandingkan tanaman lainnya.
Baca Juga: Menyingkap Peluang Pemanfaatan Limbah Cair Kelapa Sawit dalam Mitigasi Perubahan Iklim
Kemudian, Makonnen & Hoekstra (2010) juga melakukan studi perbandingan kebutuhan air produk pertanian dengan menggunakan konsep “water footprint”. Konsep ini dapat diartikan sebagai jumlah total air (air tawar) yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk pertanian.
Dari hasil penelitian tersebut, tanaman sawit membutuhkan air paling sedikit diantara tanaman minyak nabati lainnya. Sawit juga relatif sustainable dibandingkan tanaman minyak nabati lainnya karena sebagian besar air yang digunakan bersumber dari air hujan.
Jika mengacu pada penelitian-penelitian di atas, maka anggapan bahwa kelapa sawit boros air adalah salah kaprah.Kelapa sawit juga terbukti sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan juga tergolong tanaman yang paling hemat air untuk menghasilkan energi dibandingkan feedstock lainnya.
Dimana, kebutuhan air pada kelapa sawit hanya sebesar 75 m3 air untuk menghasilkan satu Giga Joule (GJ) bioenergy. Untuk menghasilkan 1 liter biodiesel, kebutuhan air yang digunakan oleh kelapa sawit hanya sebesar 5,166 liter air atau lebih rendah dibandingkan kebutuhan air kelapa, rapeseed, dan kedelai.
Selain efisiensi, kelapa sawit juga memberikan kontribusi positif dalam melestarikan tanah dan air. Pertama, kelapa sawit memiliki struktur pelepah yang berlapis serta mampu menaungi lahan (canopy cover) mendekati 100 persen pada usia dewasa sehingga dapat melindungi tanah dari pukulan langsung air hujan dan meminimalisir erosi akibat water run-off.
Kedua, kelapa sawit memiliki sistem perakaran serabut yang masif, luas, dan dalam atau membentuk sistem biopori alamiah yang memiliki kemampuan untuk menahan air (water holding capacity) melalui peningkatan infiltrasi air hujan ke dalam tanah sehingga mencegah water run-off dan menyimpan cadangan air di dalam tanah.
Baca Juga: Kontribusi Industri Sawit dalam Pencapaian SDGs Lingkungan dan Kemitraan Global