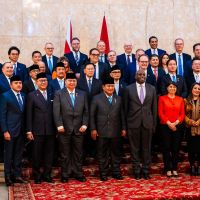Perjalanan Dato Sri Tahir sebagai salah seorang pengusaha di Indonesia begitu menarik. Tak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, Tahir juga merupakan tokoh filantropis di Indonesia.
Perjalanan Tahir sebagai konglomerat di Indonesia juga begitu panjang. Ia memiliki berbagai bisnis di bidang perbankan, tekstil hingga industri otomotif sejak awal 1980-an. Salah satu bisnisnya yang ternama adalah Grup Mayapada, yang bergerak di bidang perbankan hingga kesehatan.
Namun, jauh sebelum dirinya sukses dan menjelma jadi orang terkaya ke-7 di Indonesia yang mengantongi harta kekayaan hingga $5,2 miliar (Rp84,34 triliun), Tahir mengalami masa kecil yang cukup menyedihkan.
Pria yang memiliki nama asli Ang Tjoen Ming yang lahir di Surabaya, 26 Maret 1952 ini merupakan anak dari pasangan Ang Boen Ing dan Lie Tjien Lien. Orang tua Tahir bisa disebut sebagai orang yang kurang mampu. Dulu, orang tuanya hanyalah seorang juragan yang menyewakan becak. Tahir mengakui sendiri, dulu ia bisa hidup berkat setoran-setoran tukang becak.
“Saya adalah keluarga yang kurang mampu-lah kita sebut, orang tua cuma nyewain becak. Secara tidak langsung, sebetulnya Tukang Becak itu dengan setoran-setoran hariannya yang menghidupkan Saya,” aku Tahir, dalam wawancara eksklusif bersama Olenka, beberapa waktu lalu.
Dan, melalui pena Alberthiene Endah, suami Rosy Riady ini pun menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan mengatasi rasa minder tanpa dendam dengan wajah yang berseri.
Buku berjudul Living Sacrifice karya Alberthiene Endah merupakan sebuah biografi atau perjalanan hidup Tahir. Dalam buku tersebut, Tahir pun menceritakan tentang orang tuanya, khususnya sang ayah, Ang Boen Ing, yang disebutnya sebagai mentor hidupnya.
Baca Juga: Nama Asli Hanya Lima Huruf, Bagaimana Kisah Tahir Mendapat Gelar Dato Sri?
Masa Kecil Ayah Tahir
Dikatakan Tahir, kisah sedih masa kecilnya ternyata tak sebanding dengan masa kecil ayahnya dulu yang jauh lebih suram darinya. Ayahnya, lahir dan besar di Fujian. Fujian sendiri adalah provinsi yang sangat miskin di pantai selatan Tiongkok.
Sang ayah, Ang Boen Ing, lahir di sebuah desa kecil dalam kondisi kehidupan yang buruk akibat perang Tiongkok-Jepang pada tahun 30-an. Saat itu, banyak orang dilanda kelaparan. Belum lagi, kata Tahir, lahan pertanian saat itu harus menghadapi musim kemarau yang ekstrem. Tak pelak, jika panen bagus, masyarakat harus hati-hati menyimpan hasil panennya di rumah. Mereka tahu betul jika musim dingin akan membuat mereka sulit dalam menemukan makanan.
Gak cuma itu, kata Tahir, zaman ayahnya muda pun mencari pekerjaan sangatlah sulit. Menjadi pedagang di kalangan masyarakat miskin yang daya belinya rendah bukanlah ide yang baik pula.
“Pada saat itu, orang-orang menukar hasil panen mereka untuk bertahan hidup. Kalau yang punya kelapa, ditukar dengan sebagian dengan sayuran. Malah saking miskinnya, bahkan ada satu desa yang penduduknya tidak mampu membeli pakaian,” cerita Tahir, dalam buku Living Sacrifice karya Alberthiene Endah, dikutip Olenka, Selasa (27/8/2024).
Karena kemiskinan itulah, lanjut Tahir, pada akhirnya memaksa sebagian warga Fujian untuk berlayar ke negeri lain untuk mencari nafkah. Mereka bermimpi tentang Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Dan tak sedikit masyarakat Fujian yang berlayar ke berbagai pulau di Indonesia. Kebanyakan dari mereka pun singgah di Sumatera dan Jawa.
Menurut Tahir, saat itu sang ayah bergabung dengan rombongan warga Fujian ke Indonesia sekitar awal tahun 1940-an.
“Sebenarnya papah tidak ada niat untuk ikut perjalanan ke Indonesia. Karena kebanyakan yang pergi itu orang dewasa dan lanjut usia. Papah berusia 12 tahun saat itu, bahkan belum remaja. Tapi akhirnya ia terpaksa menempuh perjalanan jauh itu,” terang Tahir.
Jadi Pekerja Pabrik di Usia 12 Tahun Demi Membayar Utang
Tahir mengatakan, langkah sang Ayah memberanikan diri pergi mengembara ke Indonesia bukan tanpa alasan. Dia harus membantu ayahnya (kakek Tahir) untuk membayar utang yang sangat besar akibat kecanduan opium.
“Begitu jahatnya dampak candu hingga membuat kakek saya kehilangan akal dan terus menerus meminjam uang untuk membeli barang-barang jahat tersebut. Orang yang meminjamkan uang pun akhirnya marah dan memaksa kakek saya untuk melunasi utang-utangnya,” beber Tahir.
Karena itulah, kata Tahir, saking besarnya utang sang kakek, akhirnya Ang Boen Ing kecil pun disuruh datang ke Indonesia untuk bekerja dan mencari uang untuk melunasi utang-utang ayahnya.
“Saat itu papah diatur berangkat ke Indonesia dengan syarat selama 2 tahun harus bekerja di pabrik dan seluruh gajinya untuk melunasi utang kakek. Kasian papah, anak kecil yang berusia 12 tahun harus menanggung beban hidup yang begitu berat,” ujar Tahir.
Dikatakan Tahir, langkah sang ayah mengembara ke negeri itu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi seorang anak muda yang ketakutan karena harus berpisah dengan keluarganya. Bayangkan saja, anak usia 12 tahun yang belum dikatakan remaja itu harus menghadapi tantangan hidup yang begitu besar.
“Tidak banyak yang papah ceritakan pada saya tentang hal itu. Ia bahkan tidak ingat tepatnya tahun berapa ia datang ke Indonesia. Terkadang saya berpikir, mungkin itu kenangan buruk papah yang membuatnya enggan mengingatnya,” tutur Tahir.
Tahir menuturkan, sang ayah saat itu bekerja di sebuah pabrik di Surabaya dan tinggal di barak pekerja Bersama pekerja dewasa lainnya.
“Papah terpaksa tumbuh dewasa sebelum waktunya karena kehidupan yang sulit,” ujar Tahir.
Selang 2 tahun tahun bekerja, kata Tahir, sang ayah pun telah berhasil mengumpulkan uang dan utang kakek Tahir pun lunas. Namun, Ang Boen Ing pun ternyata lebih memilih tinggal di Surabaya karena saat itu pendatang asal Fujian lebih banyak di sana.
“Dia sepertinya senang tinggal di Surabaya. Cerita tentang sulitnya kehidupan di Fujian membuat papah enggan kembali ke tanah air,” tukas Tahir.
Baca Juga: Kisah Menyentuh Dato Sri Tahir di Balik Pendirian RS Mayapada
Tempati Rumah Bekas Markas Pertahanan Pejuang
Menurut Tahir, di Surabaya, terlebih saat itu di era revolusi, Ang Boen Ing mencoba segala macam pekerjaan kasar. Ia pun aktif dalam organisasi politik dan tercatat sebagai anggota Partai Nasional Tiongkok.
“Di sana, ia berkenalan dengan Tan Boen Tjoe, pemuda seusianya yang kemudian menjadi tetangganya dan lekat dengan kehidupan kami,” tutur Tahir.
Menurut Tahir, Tan Boen Tjoe merupakan pemuda tangguh yang pindah ke Indonesia akibat tekanan kemiskinan. Dia asal Fujian juga, sama dengan sang ayah. Namun, Tan Boen Tjoe beruntung bisa kuliah di universitas tersebut sehingga menjadikan dirinya memiliki kapasitas intelektual yang luar biasa.
“Di Surabaya, Tan Boen Tjoe bekerja di sebuah surat kabar berbahasa Mandarin yang berafiliasi dengan Partai Nasionalis Tiongkok. Di sanalah dia berkenalan dengan papah dan mereka aktif terlibat dalam pesta sepulang kerja. Mereka berdua ini melewati masa-masa yang mengerikan dan menyaksikan kekejaman di bawah penindasan Jepang. Termasuk adegan berdarah ketika pasukan militer Jepang terbunuh setelah kalah perang,” papar Tahir.
Lebih lanjut, Tahir pun menceritakan jika sang Ayah akhirnya memilih menjadi saudagar. Keakraban sang ayah dengan Tan Boen Tjoe pun kemudian membuahkan lokasi awal yang menjadi rumah kediaman Tahir sekeluarga.
“Saat itu cukup banyak bangunan kosong yang berubah status menjadi tidak bertuan. Akhirnya tanpa kendali dan pengaturan yang jelas, banyak orang yang menempati gedung-gedung kosong tersebut dan menjadikannya sebagai rumah. Begitulah kebingungan yang terjadi saat itu,” tutur Tahir.
Dikatakan Tahir, saat itu sang ayah dan Tan Boen Tjoe menemukan sebuah bangunan kosong di Jl. Bunguran No 19. Dilihat dari bentuknya, itu bukan rumah biasa, melainkan semacam hotel kecil satu lantai. Bangunan tersebut dibangun Belanda di atas tanah seluar kurang lebih 1.000 meter persegi. Sayangnya, bangunan tesebut kotor dan sangat rusak karena ternyata pernah digunakan sebagai markas pertahanan pejuang lokal. Ini terlihat dari banyaknya peluru di dinding dan pintu.
“Namun, ini bisa dibilang sebuah berkah untuk papah dan Tan Boen Tjoe. Karena bagi pekerja berupah minim, bangunan itu cukup untuk mereka karena tak harus membayar biaya sewa rumah. Dan lebih jauh lagi, suatu hari mereka akan menetap lama di tempat itu,” beber Tahir.
Dikatakan Tahir, saat itu, sang ayah pun berbagi rumah dengan seorang pemuda bernama Lie. Sang ayah dan Tan Boen Tjoe sepakat untuk tinggal di bangunan tersebut bertiga.
“Papah menempati sayap kiri, Tan Boen Tjoe sayap kanan, dan Lie di sayap bagian depan. Kemudahan yang mereka gunakan dan menempati rumah itu adalah dampak dari situasi pasca-perang yang kacau,” ujar Tahir.
Baca Juga: Mengenal Rosy Riady, Istri Konglomerat Dato Sri Tahir yang Gemar Beramal dan Modis Abis!
Kisah Pertemuan Orang Tua Tahir
Singkat cerita, ketiga pemuda lajang itu pun membawa kehangatan ke dalam rumah. Tan Boen Tjoe kemudian menikah dengan wanita keturunan Tionghoa dari Kalimantan bernama So Yauw Kim pada tahun 1947. Dan sang ayah menikah dengan kekasihnya, yang kemudian menjadi ibu Tahir, yakni Lie Tjien Lien pada tahun 1951.
“Saya lahir satu tahun kemudian. Lalu, mamah pun mengubah namanya menjadi Lina Sindiwaty. Jadi sejarah yang unik dimulai. Dua keluarga tinggal di rumah yang sama. Di situasi ini kemudian menyebabkan insiden emosional,” papar Tahir.
Dalam buku ini, Tahir pun menceritakan soal pertemuan sang ayah dengan ibunya. Berbeda dengan sang ayah, sang ibu menurutnya lahir dari keluarga besar kaya raya di Solo. Dia adalah putri ketiga dari 15 bersaudara. Orang tua sang ibu memiliki bisnis keramik dan keluarga sang ibu cukup popular di sektor bisnis keramik. Keluarga sang ibu juga memiliki toko yang sangat besar dan penuh dengan persediaan barang menarik untuk diimpor.
“Saya tidak yakin bagaimana orang tua saya bertemu, karena tidak ada cerita yang beritahukan kepada saya tentang hal itu. Yang saya tahu, papah pernah bilang begini, ‘Ibumu adalah wanita luar biasa yang langka. Dia rela menurunkan taraf hidupnya dan menikah dengan pria miskin sepertiku’,” tutur Tahir seraya menirukan ucapan sang ayah.
‘Sekolah Kehidupan’ Tahir
Tahir mengatakan, rumah di Jl. Bungur No 19 itu menjadi tonggak penting dalam hidupnya. Ia menghabiskan kehidupan dramatisnya di sana.
“Itu adalah bangunan bercat putih kusam dengan atap genteng tanah liat yang sangat besar. Di sanalah saya memulai hidup dan belajar tentang karakter dunia, dan mencoba memahami nasib orang miskin,” tutur Tahir.
Tahir juga mengatakan, bangunan itu pantas dikatakan sebagai sekolah kehidupannya. Dilihat dari tampilannya, kata dia, rumah tersebut mencerminkan karakter tegas dan semakin matang seiring berjalannya waktu dan peristiwa.
Meski hampir tidak pernah ada keceriaan di rumahnya tersebut, lanjut Tahir, namun berbagai gerakan dan kebisingan di dalamnya justru mencerminkan kerja keras dan kedisiplinan.
“Setiap pagi suara mamah selalu memenuhi ruangan. Dengan nada tegas dan cukup menakutkan bagi anak kecil,” cerita Tahir.
Lebih lanjut, Tahir pun mengatakan bahwa ia sangat bersyukur memiliki orang tua seperti ayahnya yang pekerja keras, serta sang ibu yang selalu menyayangi dan mengajarkannya kedisiplinan.
“Papah juga pernah mengatakan, saya adalah anak yang terlahir dari kegelapan yang diberkahi dengan anugerah yang ditunjukan oleh cahaya. Hidup saya akan bersinar terang, begitu kata papah. Saya akan sukses,” tandas Tahir.
Nah Growthmates, perjalanan hidup Tahir meraih kesuksesannya ini memang penuh dengan kerikil. Sejak usia 10 Tahun, Tahir sudah diajarkan oleh ayahnya untuk berjualan gantungan cangkir dan menjajakannya di sekitar daerah Solo. Meski hidup dalam keterbatasan, Tahir mengaku ia mendapatkan pembelajaran berharga tentang kejujuran, kerja keras, dan berbagi tanpa pamrih dari kedua orang tuanya sejak kecil.
Dalam buku ini, Tahir juga menceritakan bagaimana ia mencapai kesuksesan dengan kekuatan dari dalam diri sendiri. Menurut Tahir, membangun kekuatan diri dan tidak bergantung pada orang lain adalah hal yang sangat penting.
Sebab, jika seseorang mendapatkan kesuksesan dari hasil bersandar dengan orang lain. Maka, posisinya akan lemah dan akan hilang sewaktu-waktu atau besar kemungkinan dirampas oleh orang lain. Sebaliknya, jika kekuatan itu dibangun dari dalam diri sendiri, nobody can take it away.
Baca Juga: Kisah Dato Sri Tahir Masuk Keluarga Konglomerat Mochtar Riady