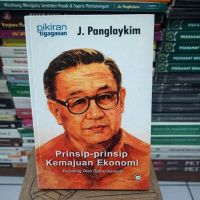Teh pertama kali ditemukan di Tiongkok oleh Kaisar Shen Nung pada 2737 SM dan berkembang menjadi bagian penting dari budaya, khususnya sejak Dinasti Tang. Tradisi ini kemudian menyebar ke Jepang dan dunia melalui jalur perdagangan, melahirkan berbagai bentuk dan ritual seperti afternoon tea di Inggris, chai di India, dan teh poci di Tegal.
Pada abad ke-17, teh menjadi komoditas bernilai tinggi dan dibudidayakan secara masif di wilayah koloni seperti India, Sri Lanka, dan Indonesia, mencerminkan bahwa teh bukan sekadar barang dagangan, tetapi juga identitas budaya. Kini, teh merupakan minuman paling banyak dikonsumsi kedua di dunia setelah air putih.
Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil teh, memiliki sejarah panjang namun kini menghadapi tantangan berat, mulai dari penurunan produktivitas, kesenjangan regenerasi petani, hingga ketatnya persaingan global.
Hari Teh Internasional yang diperingati setiap 21 Mei lalu, pertama kali diinisiasi di India pada tahun 2005 sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi buruh perkebunan. Sejak diresmikan oleh PBB pada 2019, peringatan ini tidak hanya merayakan teh sebagai minuman dunia, tetapi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun industri teh yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.
Tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan, memperkuat posisi perempuan di sektor pertanian, serta menjaga kelestarian lahan teh yang menjadi sumber penghidupan jutaan orang. Hari Teh Internasional bukan sekadar perayaan budaya, melainkan momentum untuk merumuskan masa depan industri teh dunia yang tangguh dan berkeadilan.
Produksi dan Perdagangan Teh Global
Secara global, industri teh menunjukkan pertumbuhan moderat dengan produksi mencapai 6,8 juta ton pada tahun 2023 menurut FAO. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan produksi teh hijau dan varietas non-hitam yang berhasil menutupi penurunan teh hitam, khususnya dari Sri Lanka.
Dari sisi konsumsi, permintaan teh dunia naik sekitar 2% pada tahun 2022 seiring pulihnya daya beli dan meningkatnya permintaan impor di sejumlah negara. Meski sebagian besar produksi (75%) dikonsumsi di dalam negeri masing-masing produsen, perdagangan internasional tetap bernilai tinggi dengan nilai ekspor-impor mencapai US$9,2 miliar (setara Rp150 triliun).
Asia menjadi pusat produksi utama teh dunia, dengan Tiongkok dan India menyumbang lebih dari separuh total output global, disusul Kenya dan Sri Lanka. Industri ini juga menjadi sumber penghidupan penting di negara berkembang, melibatkan sekitar 13 juta orang, di mana sembilan juta di antaranya adalah petani kecil. Petani kecil menyumbang sekitar 60% produksi global, menegaskan pentingnya dukungan terhadap mereka agar rantai pasok teh global tetap berkeadilan dan berkelanjutan.
Indonesia mengenal teh sejak era kolonial Belanda, ketika Kebun Percobaan Gambung didirikan pada tahun 1826. Sejak itu, teh menyebar luas di wilayah Priangan dan dataran tinggi Nusantara, menjadikan Hindia Belanda sebagai salah satu eksportir teh utama dunia pada akhir abad ke-19. Perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan Sumatera tidak hanya membentuk struktur ekonomi baru, tetapi juga menanamkan tradisi minum teh di masyarakat, dari teh poci di Tegal hingga upacara patehan di keraton.
Memasuki abad ke-21, meskipun posisinya melemah, Indonesia masih menempati peringkat ketujuh produsen teh dunia dengan produksi sekitar 134 ribu ton per tahun. Sekitar 60% produksi berasal dari kebun rakyat, melibatkan lebih dari 300 ribu petani. Meski kontribusi terhadap PDB nasional hanya sekitar 0,3%, teh tetap menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan di sentra-sentra produksi. Komoditas ini menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari kebun teh.
Di sektor perdagangan, nilai ekspor teh Indonesia pada tahun 2023 mencapai US$139,6 juta (sekitar Rp2,3 triliun), turun 15% dibanding tahun sebelumnya akibat melemahnya permintaan global, terutama untuk teh hitam. Penurunan ini melanjutkan tren jangka panjang sejak tahun 2010.
Pangsa pasar Indonesia turut tergeser oleh negara pesaing seperti Vietnam dan Rwanda, sementara ironisnya Indonesia mulai mengimpor teh dari luar, terutama dari Vietnam. Meskipun demikian, pasar seperti Malaysia dan Rusia tetap menjadi tujuan utama ekspor Indonesia.
Dinamika dan Tantangan Industri Teh Nasional
Industri teh Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan kompleks di sektor hulu yang memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan. Produktivitas kebun menurun drastis, terutama karena usia tanaman teh yang sudah tua—sekitar 65% berumur di atas 50 tahun. Regenerasi tenaga kerja pun menjadi isu serius; sebagian besar petani dan pemetik teh kini berusia lanjut, sementara minat generasi muda sangat rendah.
Dedek (28), petani muda dari Garut, mengungkapkan bahwa anak muda lebih memilih menanam sayur karena dianggap lebih menguntungkan daripada bertani teh.
Harga jual daun teh di tingkat petani yang rendah, berkisar antara Rp1.800–2.400/kg, juga menjadi penyebab lemahnya insentif untuk merawat kebun. Rantai pasok yang panjang dan dominasi tengkulak membuat posisi tawar petani rendah, sehingga margin keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak pengolah dan distributor. Selain itu, perubahan iklim menyebabkan gangguan pada pola tanam dan hasil panen.
Di tengah tantangan tersebut, hilirisasi menjadi peluang strategis bagi industri teh nasional. Produk olahan seperti teh celup, ekstrak, dan minuman siap saji kini menyumbang sekitar 40% ekspor teh Indonesia dan menunjukkan pertumbuhan positif. Industri besar teh telah berhasil menguasai pasar domestik serta merambah pasar luar negeri.
Produk teh dalam kemasan siap minum (ready to drink) kini menjadi tulang punggung serapan daun teh lokal. Ini menandakan bahwa transformasi dari komoditas curah ke produk bernilai tambah menjadi langkah logis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing industri teh Indonesia.
Selain minuman, inovasi teh premium dan organik mulai mendapat tempat di pasar global. Merek lokal seperti Javara berhasil mengekspor teh bersertifikat organik ke Amerika Serikat dan Eropa dengan harga berkali lipat dari produk massal.
Diversifikasi juga terlihat pada pemanfaatan ekstrak teh untuk industri kosmetik dan kesehatan. Produk-produk seperti teh rosella, teh jamu herbal, dan matcha lokal memiliki potensi besar untuk masuk ke pasar teh kesehatan yang terus tumbuh. Dengan memperkuat keunikan lokal, Indonesia dapat mengembangkan produk niche yang bernilai tinggi dan berdaya saing global.
Strategi pemasaran juga perlu ditingkatkan. Edukasi konsumen, kampanye digital, serta desain kemasan modern penting untuk menjangkau generasi muda. Gerakan "Nasionalisme Teh Nusantara" dan "Teh untuk Bumi" dari Gabungan Pengusaha Teh Indonesia merupakan contoh upaya membangun kesadaran terhadap teh lokal dan keberlanjutan.
Terakhir, diversifikasi pasar ekspor menjadi krusial. Indonesia perlu memperluas jangkauan ke negara-negara yang menghargai kualitas dan keberlanjutan, seperti Jepang, Eropa Barat, dan Timur Tengah.
Kolaborasi dalam Revitalisasi Teh
Mengatasi tantangan kompleks industri teh Indonesia memerlukan sinergi kuat antar-pemangku kepentingan. Pemerintah, BUMN, dan lembaga litbang harus bekerja sama dalam mendorong transformasi sektor teh dari hulu ke hilir. Program Peremajaan Kebun Teh Rakyat (P2KTR) sejak 2023 menjadi salah satu contoh langkah konkret yang patut diapresiasi.
Dengan dukungan KUR berbunga rendah, program ini telah menunjukkan dampak positif di beberapa daerah, seperti Wonosobo, yang mencatat peningkatan produktivitas dua kali lipat setelah penggunaan varietas unggul Tambi 1 dan Tambi 2 yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (sekarang menjadi BRMP). Ini membuktikan bahwa intervensi terarah berbasis teknologi mampu meningkatkan hasil dan pendapatan petani.
Peran BUMN seperti PTPN juga sangat penting, khususnya dalam modernisasi perkebunan dan efisiensi produksi. Penerapan precision agriculture berbasis IoT di PTPN VIII menjadi contoh bahwa digitalisasi pertanian bisa meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko gagal panen. Model smart plantation ini perlu dikembangkan lebih luas, termasuk di perkebunan rakyat melalui kemitraan strategis.
Di saat yang sama, lembaga litbang seperti BRMP Tanaman Industri dan Penyegar dan perguruan tinggi memainkan peran kunci dalam menghadirkan varietas unggul serta inovasi proses, seperti bioreaktor fermentasi cepat yang mempersingkat waktu produksi dan meningkatkan efisiensi.
Dukungan kebijakan yang berpihak pada petani juga menjadi kunci. Pemerintah perlu mempertimbangkan insentif seperti harga acuan dan subsidi input agar petani tetap terdorong bertahan di sektor teh. Momen Hari Teh Internasional 2025 menjadi pengingat bahwa secangkir teh tidak hanya soal minuman, tetapi kisah tentang kerja keras, budaya, dan harapan masa depan.