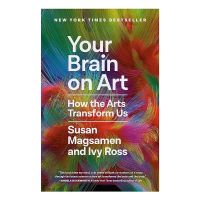Respons publik terhadap bencana sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi yang menyertainya. Informasi yang terlambat, tidak akurat, atau minim empati berpotensi memicu kepanikan sekaligus menghambat distribusi bantuan. Sebaliknya, komunikasi yang jelas, terverifikasi, dan berpihak pada korban mampu memperkuat rasa aman serta mempercepat koordinasi lintas pihak di lapangan.
Isu ini mengemuka dalam acara Good Talk Off Air bertajuk Komunikasi Bencana: Merespons Bencana dengan Tepat dan Empati yang digelar di Sasana Budaya Dompet Dhuafa, Jakarta, Rabu (17/12). Kegiatan ini merupakan kolaborasi GoodNews From Indonesia, Perhumas, dan Dompet Dhuafa, dengan menghadirkan pakar komunikasi bencana Dr. Muhammad Hidayat, M.I.Kom, Ketua Disaster Crisis Center Dompet Dhuafa Udhi Tri Kurniawan, serta jurnalis senior Kompas Ahmad Arif.
Dr. Muhammad Hidayat menegaskan bahwa komunikasi bencana bukan sekadar pelengkap teknis, melainkan fondasi utama ketangguhan masyarakat. Menurutnya, kegagalan komunikasi pada fase awal hampir selalu berujung pada persoalan yang lebih besar di tahap berikutnya.
“Kalau komunikasi risiko di pra-bencana sudah bermasalah, saya bisa meyakini fase darurat dan pasca-bencana juga akan bermasalah,” ujar Hidayat.
Ia menjelaskan, manajemen bencana terdiri dari tiga fase utama, yakni pra-bencana, fase darurat, dan pasca-bencana. Pada fase pra-bencana, komunikasi risiko menjadi kunci untuk menyampaikan potensi ancaman agar masyarakat dapat bersiap dan meminimalkan kerugian. Fase darurat menuntut komunikasi krisis yang cepat, akurat, jujur, dan empatik. Sementara pada fase pasca-bencana, komunikasi berperan membangun resiliensi, yakni kemampuan masyarakat untuk bangkit dan beradaptasi menuju kondisi yang lebih baik.
Baca Juga: Dompet Dhuafa Gandeng Musisi dan Ruang Kreatif Satukan Energi untuk Pemulihan Sumatra dan Aceh
Hidayat juga menyoroti persoalan klasik komunikasi bencana di Indonesia, terutama lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Ia menyebut tantangan 3K—komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi—masih kerap terjadi di lapangan.
Ia mencontohkan, peringatan dini yang disampaikan lembaga teknis sering kali tidak diikuti langkah mitigasi yang jelas di tingkat daerah. Akibatnya, masyarakat menerima informasi yang saling bertentangan dan memicu kebingungan.
“Kita sering panik di fase darurat karena identifikasi risiko di awal tidak dilakukan dengan jelas. Akibatnya, pemerintah dan masyarakat sama-sama gagap,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan berbasis data. Memberikan harapan tanpa dasar informasi yang kuat justru berpotensi memicu kemarahan publik ketika realitas di lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan.
Diskusi juga menyinggung tingginya partisipasi publik dalam membantu korban bencana. Ketua Disaster Crisis Center Dompet Dhuafa, Udhi Tri Kurniawan, menilai partisipasi tersebut merupakan kekuatan besar, namun harus dikelola dengan komunikasi yang tepat.
“Tidak semua orang siap berada di area bencana. Keterlibatan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan di lapangan,” ujar Udhi.
Baca Juga: Dompet Dhuafa Luncurkan IKON, Industri Komunal Penggerak Ekonomi Cirangkong
Misalnya, kehadiran relawan tanpa keterampilan khusus pada situasi tertentu justru dapat membebani sistem logistik dan koordinasi. Karena itu, edukasi publik menjadi kunci agar masyarakat memahami bentuk bantuan yang paling dibutuhkan, termasuk dukungan dari jarak jauh melalui donasi, penggalangan informasi, dan penyebaran pesan yang benar.
Dari perspektif media, jurnalis senior Kompas Ahmad Arif menilai lemahnya komunikasi risiko sejak awal turut berkontribusi pada kekacauan penanganan bencana. Ia menyoroti kecenderungan media yang lebih menitikberatkan pada korban dan dampak visual tanpa diimbangi edukasi mitigasi.
“Ketika komunikasi risiko dan komunikasi krisis buruk, pemberitaan justru memperlebar jarak antara narasi dan realitas di lapangan,” ujarnya.
Menurut Ahmad Arif, media seharusnya hadir sebelum bencana terjadi dengan membangun literasi risiko, sehingga publik tidak hanya bereaksi saat bencana datang, tetapi juga memahami ancaman dan langkah pencegahannya.
Baca Juga: Diaudit Total Terkait Bencana Sumatra, Benarkah PT Toba Pulp Lestari Milik Luhut?
Para pembicara juga menyinggung praktik baik di negara lain, seperti Jepang, yang menjadikan memori bencana sebagai bagian dari pembelajaran kolektif. Jepang mendokumentasikan bencana secara rinci, membangun museum, serta mengintegrasikan edukasi kebencanaan ke dalam kehidupan sehari-hari.
“Di Jepang, bencana tidak dilupakan. Mereka membangun disaster memory agar kesalahan tidak terulang,” kata Hidayat.
Ia menilai Indonesia perlu memperkuat peran akademisi, media, pemerintah, dan masyarakat secara bersama untuk membangun sistem komunikasi bencana yang konsisten dari hulu ke hilir.
Dengan begitu, seluruh pembicara sepakat, inti komunikasi bencana terletak pada empati, kejelasan, dan kejujuran berbasis data. Dengan komunikasi yang tepat, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bagian dari solusi, mulai dari menyaring informasi hingga menyebarkan pesan secara bertanggung jawab.