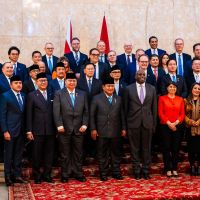Kondisi gagal ginjal kronik (GGK) bisa menimpa siapa saja, tanpa memandang usia atau jenis kelamin.
Namun, menurut data Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI), perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit ginjal kronik dibandingkan pria. Beberapa studi menunjukkan prevalensinya mencapai sekitar 14% pada perempuan, sementara pada pria sekitar 12%.
Selain faktor gaya hidup, komplikasi kehamilan seperti preeklampsia dan eklampsia juga menjadi penyebab penting munculnya gagal ginjal pada perempuan.
Itulah yang dialami A (39 tahun), seorang perempuan asal Jawa Tengah, yang kisah hidupnya menjadi cermin betapa rapuhnya keseimbangan antara harapan dan kebijakan medis.
Dari Kehilangan ke Keajaiban
Tahun 2014 menjadi titik balik dalam hidup A. Saat itu, di usia 28 tahun, ia menjalani kehamilan yang berakhir tragis. Bayinya lahir prematur dan hanya bertahan beberapa hari. Tak lama berselang, A divonis menderita gagal ginjal kronik akibat eklampsia.
Dokter menyarankan transplantasi ginjal sebagai jalan terbaik. Namun, pencarian donor tidak mudah.
Ayahnya, yang memiliki golongan darah O seperti dirinya, juga mengalami gagal ginjal dan harus menjalani hemodialisis. Ibunya bergolongan darah AB, sehingga tidak cocok sebagai donor. A pun harus bertahan dengan hemodialisis selama dua setengah tahun.
Hingga suatu hari, terjadi sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Ibunya bersikeras memeriksa ulang golongan darahnya, meyakini mungkin ada kekeliruan. Hasilnya mengejutkan semua pihak: golongan darah sang ibu berubah dari AB menjadi O.
“Kami pergi ke empat laboratorium berbeda untuk memastikan, dan semuanya menunjukkan hasil yang sama,” cerita A dengan mata berbinar.
Secara medis, perubahan golongan darah semacam itu nyaris mustahil karena sifatnya genetik dan stabil. Namun, bagi A dan keluarganya, hal itu adalah mukjizat.
Pada Mei 2017, ia menjalani transplantasi ginjal di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah, seluruh biayanya ditanggung BPJS Kesehatan. Setelah operasi, kondisinya pulih dan hidupnya kembali berjalan normal.
Selama delapan tahun pascatransplantasi, A menjalani hidup dengan penuh syukur. Kadar kreatininnya stabil antara 0,8–1,2, berkat enam jenis obat yang dikonsumsi setiap hari, termasuk obat imunosupresan originator, yang berfungsi menekan sistem imun agar tubuh tidak menolak organ baru.
Namun, kedamaian itu terusik pada September 2024, ketika pemerintah mengganti obat imunosupresan originator yang ia gunakan menjadi versi non-originator dengan alasan efisiensi anggaran. Dampaknya segera terasa.
Kadar kreatininnya yang semula stabil perlahan naik dari 1,3 menjadi 1,4, lalu 1,5, hingga mencapai 1,6 pada Agustus 2025, melampaui batas aman.
A bukan satu-satunya yang mengalami hal itu. Berdasarkan survei Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terhadap 23 pasien, 39% mengalami peningkatan kadar kreatinin, dan 13% di antaranya melampaui batas normal. Sementara itu, 52% pasien melaporkan efek samping setelah mengonsumsi imunosupresan non-originator.
Untuk menekan kadar kreatinin, dokter menaikkan dosis methylprednisolone, salah satu obat pendamping bagi pasien transplantasi.
Langkah itu memang menurunkan kadar kreatinin, namun memicu efek samping serius, yakni gula darah A melonjak hingga 395 mg/dL, padahal sebelumnya ia tidak memiliki riwayat diabetes. Ia pun harus dirawat dan menjalani terapi insulin.
“Rasanya seperti bermain dengan nyawa kami,” kata A.
“Dua nyawa sudah dipertaruhkan di meja operasi. Semua perjuangan itu seolah diabaikan demi menghemat anggaran dengan mengganti obat yang belum tentu kualitasnya sama," sambungnya.
Setelah melalui berbagai advokasi bersama KPCDI, A akhirnya kembali mendapat obat originator pada Agustus 2025. Hasilnya hampir instan, kreatinin turun menjadi 1,1 hanya dalam beberapa minggu.
Baca Juga: 7 Gejala Awal Kanker Ginjal yang Sering Terlihat Sepele