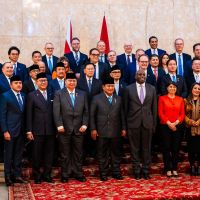Perjalanan Dato Sri Tahir sebagai salah seorang pengusaha di Indonesia begitu menarik. Tak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, Tahir juga merupakan tokoh filantropis di Indonesia.
Perjalanan Tahir sebagai konglomerat di Indonesia juga begitu panjang. Ia memiliki berbagai bisnis di bidang perbankan, tekstil hingga industri otomotif sejak awal 1980-an. Salah satu bisnisnya yang ternama adalah Grup Mayapada, yang bergerak di bidang perbankan hingga kesehatan.
Namun, jauh sebelum dirinya sukses dan menjelma jadi orang terkaya ke-7 di Indonesia yang mengantongi harta kekayaan hingga $5,2 miliar (Rp84,34 triliun), Tahir mengalami masa kecil yang cukup menyedihkan.
Pria yang memiliki nama asli Ang Tjoen Ming yang lahir di Surabaya, 26 Maret 1952 ini merupakan anak dari pasangan Ang Boen Ing dan Lie Tjien Lien. Orang tua Tahir bisa disebut sebagai orang yang kurang mampu. Dulu, orang tuanya hanyalah seorang juragan yang menyewakan becak. Tahir mengakui sendiri, dulu ia bisa hidup berkat setoran-setoran tukang becak.
“Saya adalah keluarga yang kurang mampu-lah kita sebut, orang tua cuma nyewain becak. Secara tidak langsung, sebetulnya Tukang Becak itu dengan setoran-setoran hariannya yang menghidupkan Saya,” aku Tahir, dalam wawancara eksklusif bersama Olenka, beberapa waktu lalu.
Dan, melalui pena Alberthiene Endah, suami Rosy Riady ini pun menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan mengatasi rasa minder tanpa dendam dengan wajah yang berseri.
Buku berjudul Living Sacrifice karya Alberthiene Endah merupakan sebuah biografi atau perjalanan hidup Tahir. Dalam buku tersebut, Tahir pun menceritakan tentang orang tuanya, khususnya sang ayah, Ang Boen Ing, yang disebutnya sebagai mentor hidupnya.
Baca Juga: Nama Asli Hanya Lima Huruf, Bagaimana Kisah Tahir Mendapat Gelar Dato Sri?
Masa Kecil Ayah Tahir
Dikatakan Tahir, kisah sedih masa kecilnya ternyata tak sebanding dengan masa kecil ayahnya dulu yang jauh lebih suram darinya. Ayahnya, lahir dan besar di Fujian. Fujian sendiri adalah provinsi yang sangat miskin di pantai selatan Tiongkok.
Sang ayah, Ang Boen Ing, lahir di sebuah desa kecil dalam kondisi kehidupan yang buruk akibat perang Tiongkok-Jepang pada tahun 30-an. Saat itu, banyak orang dilanda kelaparan. Belum lagi, kata Tahir, lahan pertanian saat itu harus menghadapi musim kemarau yang ekstrem. Tak pelak, jika panen bagus, masyarakat harus hati-hati menyimpan hasil panennya di rumah. Mereka tahu betul jika musim dingin akan membuat mereka sulit dalam menemukan makanan.
Gak cuma itu, kata Tahir, zaman ayahnya muda pun mencari pekerjaan sangatlah sulit. Menjadi pedagang di kalangan masyarakat miskin yang daya belinya rendah bukanlah ide yang baik pula.
“Pada saat itu, orang-orang menukar hasil panen mereka untuk bertahan hidup. Kalau yang punya kelapa, ditukar dengan sebagian dengan sayuran. Malah saking miskinnya, bahkan ada satu desa yang penduduknya tidak mampu membeli pakaian,” cerita Tahir, dalam buku Living Sacrifice karya Alberthiene Endah, dikutip Olenka, Selasa (27/8/2024).
Karena kemiskinan itulah, lanjut Tahir, pada akhirnya memaksa sebagian warga Fujian untuk berlayar ke negeri lain untuk mencari nafkah. Mereka bermimpi tentang Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Dan tak sedikit masyarakat Fujian yang berlayar ke berbagai pulau di Indonesia. Kebanyakan dari mereka pun singgah di Sumatera dan Jawa.
Menurut Tahir, saat itu sang ayah bergabung dengan rombongan warga Fujian ke Indonesia sekitar awal tahun 1940-an.
“Sebenarnya papah tidak ada niat untuk ikut perjalanan ke Indonesia. Karena kebanyakan yang pergi itu orang dewasa dan lanjut usia. Papah berusia 12 tahun saat itu, bahkan belum remaja. Tapi akhirnya ia terpaksa menempuh perjalanan jauh itu,” terang Tahir.
Jadi Pekerja Pabrik di Usia 12 Tahun Demi Membayar Utang
Tahir mengatakan, langkah sang Ayah memberanikan diri pergi mengembara ke Indonesia bukan tanpa alasan. Dia harus membantu ayahnya (kakek Tahir) untuk membayar utang yang sangat besar akibat kecanduan opium.
“Begitu jahatnya dampak candu hingga membuat kakek saya kehilangan akal dan terus menerus meminjam uang untuk membeli barang-barang jahat tersebut. Orang yang meminjamkan uang pun akhirnya marah dan memaksa kakek saya untuk melunasi utang-utangnya,” beber Tahir.
Karena itulah, kata Tahir, saking besarnya utang sang kakek, akhirnya Ang Boen Ing kecil pun disuruh datang ke Indonesia untuk bekerja dan mencari uang untuk melunasi utang-utang ayahnya.
“Saat itu papah diatur berangkat ke Indonesia dengan syarat selama 2 tahun harus bekerja di pabrik dan seluruh gajinya untuk melunasi utang kakek. Kasian papah, anak kecil yang berusia 12 tahun harus menanggung beban hidup yang begitu berat,” ujar Tahir.
Dikatakan Tahir, langkah sang ayah mengembara ke negeri itu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi seorang anak muda yang ketakutan karena harus berpisah dengan keluarganya. Bayangkan saja, anak usia 12 tahun yang belum dikatakan remaja itu harus menghadapi tantangan hidup yang begitu besar.
“Tidak banyak yang papah ceritakan pada saya tentang hal itu. Ia bahkan tidak ingat tepatnya tahun berapa ia datang ke Indonesia. Terkadang saya berpikir, mungkin itu kenangan buruk papah yang membuatnya enggan mengingatnya,” tutur Tahir.
Tahir menuturkan, sang ayah saat itu bekerja di sebuah pabrik di Surabaya dan tinggal di barak pekerja Bersama pekerja dewasa lainnya.
“Papah terpaksa tumbuh dewasa sebelum waktunya karena kehidupan yang sulit,” ujar Tahir.
Selang 2 tahun tahun bekerja, kata Tahir, sang ayah pun telah berhasil mengumpulkan uang dan utang kakek Tahir pun lunas. Namun, Ang Boen Ing pun ternyata lebih memilih tinggal di Surabaya karena saat itu pendatang asal Fujian lebih banyak di sana.
“Dia sepertinya senang tinggal di Surabaya. Cerita tentang sulitnya kehidupan di Fujian membuat papah enggan kembali ke tanah air,” tukas Tahir.
Baca Juga: Kisah Menyentuh Dato Sri Tahir di Balik Pendirian RS Mayapada